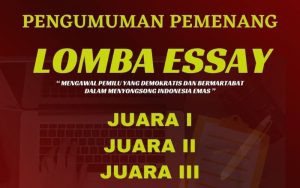Di tengah cakrawala Eropa yang menggelap, ketika dunia menahan napas di ambang konflik paling destruktif dalam sejarah, sebuah gestur anomali terjadi. Mesin perang Jerman, di bawah komando absolut Adolf Hitler, bersiap untuk melumat benua. Namun, ribuan mil jauhnya, seorang pria yang kehidupannya adalah antitesis dari kekerasan—seorang arsitek perlawanan sipil—merasa terpanggil untuk melakukan intervensi yang hampir mustahil.
Mahatma Gandhi, sang rasul Ahimsa, mengambil pena. Ia tidak menulis kepada sekutu; ia menulis langsung kepada sang agresor. Ini adalah kisah tentang sebuah Surat Perdamaian yang luar biasa, sebuah korespondensi yang menantang logika politik dan militer.
Apa yang ditulis oleh seorang suci kepada seorang tiran? Bagaimana ia menyapanya?
Mari kita selami arsip ganjil ini, sebuah dialog antara keyakinan moral yang radikal dan kebrutalan kekuasaan yang tak tertandingi, untuk memahami keberanian—atau kenaifan—di balik upaya menghentikan badai dengan sepucuk surat.
I. Di Ambang Jurang Kehancuran: Latar Belakang Korespondensi Mustahil
A. Gema Perang di Cakrawala Eropa
Tahun adalah 1939. Udara di benua Eropa terasa berat, sarat dengan anteseden konflik yang tak terhindarkan. Politik aneksasi dan retorika agresif yang diorkestrasi oleh Kanselir Jerman, Adolf Hitler, telah mendorong dunia ke tepi jurang. Setelah aneksasi Austria dan pendudukan Cekoslowakia, Polandia kini berada dalam bidikan. Mesin perang Jerman, Wehrmacht, sedang bersiap. Eskalasi militer ini bukan lagi sekadar manuver politik; itu adalah prolog dari sebuah pertumpahan darah global yang akan mendefinisikan ulang abad ke-20. Di tengah ketegangan yang memuncak ini, dunia menahan napas, mengantisipasi langkah Hitler selanjutnya. Diplomasi konvensional telah gagal, dan jalur komunikasi antar negara besar membeku dalam kecurigaan.
B. Filosofi Ahimsa Menghadapi Realitas Brutal
Ribuan mil jauhnya, di India yang masih dalam cengkeraman kolonialisme Inggris, seorang pria kurus yang hanya berbalut kain katun mengamati perkembangan ini dengan kegelisahan mendalam. Mohandas Karamchand Gandhi, yang dijuluki Mahatma atau “Jiwa Agung,” adalah antitesis dari segala sesuatu yang direpresentasikan oleh Hitler. Jika Hitler adalah perwujudan kekerasan terorganisir dan supremasi rasial, Gandhi adalah arsitek Satyagraha—kekuatan kebenaran—dan penganut teguh Ahimsa, prinsip non-kekerasan absolut. Bagi Gandhi, kekerasan bukanlah solusi, melainkan sumber masalah itu sendiri. Menyaksikan bayang-bayang perang yang semakin memanjang, Gandhi merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang, bagi banyak orang, tampak sangat naif, bahkan utopis: ia memutuskan untuk menulis surat.
II. “Sahabatku Terkasih”: Analisis Teks dan Niat Sang Mahatma
A. Surat Pertama (1939): Seruan Kemanusiaan yang Ringkas
Pada tanggal 23 Juli 1939, hanya beberapa minggu sebelum invasi ke Polandia yang memicu Perang Dunia II, Gandhi mengambil pena. Surat itu dialamatkan kepada “Herr Hitler, Berlin, Jerman.” Yang paling mencolok, dan hingga kini paling banyak dibicarakan, adalah sapaan pembukanya: “Dear friend,” atau “Sahabatku terkasih.”
Ironi historis dari sapaan ini begitu menusuk. Gandhi, dalam upayanya untuk menjangkau kemanusiaan sang diktator, menggunakan terminologi persahabatan kepada orang yang akan segera menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Surat itu sendiri sangat singkat. Gandhi memohon kepada Hitler, sebagai satu-satunya orang di dunia yang tampaknya mampu mencegah perang yang akan “mereduksi kemanusiaan ke kondisi buas,” untuk mempertimbangkan kembali tindakannya. Dia tidak berdebat tentang politik atau perbatasan; dia mengajukan premis moral. Gandhi menulis bahwa ia sengaja menghindari metode banding konvensional, memilih untuk mengajukan permohonan atas nama kemanusiaan. Itu adalah upaya murni Ahimsa dalam bentuk tulisan, sebuah taruhan spiritual bahwa hati nurani masih ada di dalam diri sang Führer.
B. Surat Kedua (1940): Peringatan yang Lebih Panjang dan Putus Asa
Surat pertama tidak pernah sampai ke Berlin. Surat itu dicegat oleh Pemerintah Inggris, yang menganggap intervensi Gandhi tidak membantu secara diplomatik. Namun, Gandhi tidak menyerah. Pada Malam Natal, 24 Desember 1940, ia menulis lagi. Situasinya telah berubah secara drastis. Perang telah berkecamuk selama lebih dari setahun. Polandia telah jatuh. Prancis telah takluk. Pertempuran di Inggris sedang mencapai puncaknya.
Surat kedua ini jauh lebih panjang dan nadanya lebih mendesak, hampir putus asa, namun tetap mempertahankan kesopanan yang teguh. Gandhi kembali menggunakan sapaan “Dear friend.” Kali ini, ia lebih eksplisit. Ia mengakui bahwa tindakannya mungkin lancang, tetapi ia harus melakukannya. Gandhi dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak ragu tentang keberanian atau pengabdian Hitler pada tanah airnya, tetapi ia mengkritik metodologi Hitler sebagai “monster.” Dengan kejujuran yang luar biasa, Gandhi bahkan menyamakan imperialisme Inggris dengan Nazisme, menyebut keduanya sebagai bentuk kekerasan, meskipun ia mengakui metode Hitler jauh lebih brutal. Ia mengakhiri surat itu dengan menawarkan metode Satyagraha sebagai alternatif yang lebih mulia untuk mencapai tujuan, sebuah cara perlawanan tanpa menimbulkan penderitaan pada orang lain.
III. Gema di Ruang Hampa: Dampak (atau Ketiadaannya) dan Relevansi Abadi
A. Surat yang Tak Terkirim dan Tembok Keheningan Berlin
Sama seperti surat pertama, surat kedua juga tidak pernah mencapai tujuannya. Surat itu sekali lagi diintervensi oleh otoritas Inggris. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Adolf Hitler pernah membaca salah satu dari dua surat yang ditujukan kepadanya oleh Gandhi. Korespondensi itu, pada kenyataannya, adalah sebuah monolog. Pesan perdamaian dari eksponen non-kekerasan terbesar di dunia gagal menembus tembok birokrasi, apalagi kesadaran ideologis sang diktator. Dari perspektif pragmatisme politik, upaya Gandhi adalah kegagalan total. Perang terus berlanjut, mencapai tingkat kebrutalan yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh Gandhi ketika ia menulis surat-surat itu.
B. Paradoks Keberanian: Warisan Dialog Gandhi dengan Tirani
Lalu, mengapa kita masih membahas surat-surat ini? Kegagalan praktis mereka tidak mengurangi signifikansi filosofis mereka. Korespondensi ini mewakili benturan paling ekstrem antara dua ideologi yang berlawanan di abad ke-20: kekuatan jiwa melawan kekuatan baja. Surat-surat itu menunjukkan konsistensi Gandhi yang tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsipnya. Dia percaya bahwa Ahimsa adalah hukum universal, yang berlaku bahkan untuk tiran terburuk sekalipun.
Tindakan menulis surat kepada Hitler, terutama dengan sapaan “Sahabatku terkasih,” sering dilihat sebagai naif. Namun, itu juga bisa dilihat sebagai tindakan keberanian moral yang radikal. Gandhi menolak untuk mendehumanisasi lawannya, bahkan ketika lawannya sedang aktif mendehumanisasi seluruh ras. Surat-surat itu tetap ada bukan sebagai artefak diplomasi yang sukses, tetapi sebagai bukti dari sebuah keyakinan. Mereka adalah gema di ruang hampa, sebuah pengingat abadi akan paradoks mencoba berdialog dengan tirani absolut, dan sebuah kesaksian atas keyakinan satu orang bahwa kemanusiaan, betapapun terpendamnya, selalu layak untuk diajak bicara.